 (ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari)
(ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari)
ARTIKEL Willy Aditya, Ketua Komisi XIII DPR RI dan pengusul RUU tentang Perbukuan, di Media Indonesia (14/8), mewakili kegundahan para pelaku perbukuan tentang suramnya dunia buku di Tanah Air. Mereka tak kurang lantang tentang hal ini, tetapi tak cukup ditanggapi. Suara mereka dipandang sebagai vested interest industri belaka. Ini paradoks perbukuan kita: Buku diakui dalam hati sebagai aras akal budi yang harus dibangun, tetapi ekosistemnya tidak didukung dengan sepenuh hati.
Indonesia adalah negara terbesar dalam industri perbukuan di ASEAN. Lebih dari 100 ribu judul buku terbit setiap tahun. Ada sekitar 25 ribu institusi (penerbit komersial, lembaga pendidikan atau riset, dll) yang terdaftar sebagai pemohon ISBN. Asosiasi penerbit buku Ikapi memiliki lebih dari 950 anggota aktif (bandingkan dengan Vietnam yang hanya 80 penerbit dan Malaysia 160 penerbit). Namun, secara paradoksal pula, di Indonesia, puluhan penerbit mati setiap tahun dan toko-toko buku tutup.
Sampai saat ini, amanat Undang-Undang No 3 Tahun 2017 tentang kehadiran lembaga yang mengorkestrasi seluruh kegiatan perbukuan nasional tidak pernah terwujud. Nomenklatur literasi di Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) malah tak ada lagi. Sementara itu, anggaran untuk pengembangan industri penerbitan sebagai subsektor ekonomi kreatif di Kementerian Ekraf amat minim karena Bappenas menilai kontribusi bidang ekonomi kreatif terhadap PDB nasional rendah. Anehnya, saat kontribusi PDB dijadikan acuan anggaran, kementerian ini sekarang justru berada di bawah Kemenko Pemberdayaan Masyarakat alih-alih Kemenko Bidang Perekonomian seperti pada era Kemenparekraf.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan mengandung dua bias utama. Pertama, bias terhadap buku pelajaran sekolah, terutama buku teks. Terdapat 15 pasal pada UU ini yang mengatur buku pendidikan dan hanya satu pasal yang membicarakan buku umum. Pada ketentuan turunannya, PP No 75 Tahun 2019, terlihat fokus pemerintah pada pembenahan area buku pendidikan dan mengabaikan buku-buku yang beredar di pasar umum.
Sebagian besar regulasi turunan dari UU No 3 Tahun 2017 dan PP No 75 Tahun 2019 juga berada pada wilayah buku pendidikan, antara lain Permendikbudristek No 25 Tahun 2022 tentang Penilaian Buku Pendidikan, Peraturan Kepala BSKAP No 030/P/2022 tentang Pedoman Perjenjangan Buku, dan Peraturan Kepala BSKAP Nomor 039/H/P/2022 tentang Pedoman Penilaian Buku Pendidikan.
Bias kedua ialah terhadap hulu perbukuan, terutama pada para pelaku penerbitan, dan mengabaikan hilir perbukuan yakni pembaca buku. Dari tujuh tanggung jawab pemerintah terhadap ekosistem perbukuan, lima hal berkaitan dengan tahap penerbitan buku. Satu hal tentang promosi budaya. Satu lagi berbicara tentang minat baca. Namun, ini pun merujuk pada peran penerbit, yaitu ‘Melalui pengadaan naskah buku yang bermutu’.
Undang-undang ini tak memasukkan pembaca sebagai bagian dari ekosistem perbukuan. Tanggung jawab berat berada pada penulis, editor, penerjemah, penyadur, desainer, ilustrator, pencetak buku, penerbit, pengembang buku elektronik, dan toko buku. Kendati mereka menerima tanggung jawab tersebut—untuk menerbitkan buku 3M (bermutu, murah, merata) sesuai amanat UU—apa artinya jika buku-buku itu tak pernah sampai ke tangan pembaca karena masyarakat tidak memiliki budaya baca atau kesulitan mengakses bahan bacaan.
UU LITERASI
Paradoks lainnya ada pada masyarakat kita. Tingkat literasi nasional melampaui 96%. Namun, ini adalah literacy dalam pengertian melek huruf sebagai lawan kata illiteracy (buta huruf). Merujuk pada Miller dan Mc Kenna (World Literacy: How Countries Rank and Why it Matters, 2016), hal yang lebih utama ialah literacy sebagai kebiasaan membaca, sebagai lawan kata dari aliteracy (melek huruf tapi tidak membaca).
Ikapi tidak meragukan minat baca masyarakat Indonesia. Dalam setiap kegiatan berbagi buku, anak-anak berebut buku dan mereka memiliki preferensi yang baik tentang buku-buku yang hendak dibaca. Namun, minat baca saja tidak cukup. Masyarakat memerlukan akses terhadap bahan bacaan dan pembinaan kebiasaan membaca untuk sampai pada tujuan kapasitas literasi, yakni kemampuan berpikir kritis dalam mengakses informasi.
Willy menyitir indeks literasi kita dalam PISA (Programme for International Student Assessment) yang terpuruk di papan bawah di antara negara-negara anggota dan mitra OECD. Sesungguhnya dalam berbagai parameter lain, posisi Indonesia juga menyedihkan. Berdasarkan PIRLS (Progress in International Reading Literacy Studies), anak-anak kelas 4 SD kita berada pada peringkat 42 dari 45 negara. Sementara itu, berdasarkan PIAC (The Programme for International Assessment of Adult Competencies), warga dewasa kita menduduki peringkat terbawah dari 35 negara peserta yang diriset.
Di level nasional, tak satu provinsi pun di Indonesia berada pada kategori literasi tinggi pada Indeks Aktivitas Literasi Baca (Alibaca) versi Kemendikbud 2019. Sembilan provinsi tergolong sedang, 24 provinsi pada kategori rendah, dan 1 provinsi sangat rendah. Adapun hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) 2016 menunjukkan secara nasional hanya 6,06% siswa yang memiliki kompetensi baik dalam literasi membaca. Sebanyak 47,11% pada posisi cukup dan 46,83% kurang.
Bagi sebuah bangsa, indeks literasi amat penting. World Economic Forum menyebut literasi sebagai kecakapan abad ke-21 yang dibutuhkan oleh bangsa untuk meningkatkan kualitas hidup. Literasi baca-tulis berada pada kategori kecakapan fundamental bersama literasi numerasi dan sains. Skor Indonesia untuk ketiga literasi itu mengalami kemerosotan sepanjang periode 2015 hingga 2022, dan kondisi terparah dialami literasi baca-tulis (turun 38 poin dari 397 ke 359) berbanding literasi numerasi (dari 386 ke 366) dan literasi sains (dari 403 ke 383).
Merevisi UU Sistem Perbukuan dapat memperbaiki bias hulu perbukuan maupun bias buku pelajaran. Namun, mengembangkan sebuah UU yang mendorong peningkatan kecakapan literasi tampaknya lebih strategis. Literasi jauh lebih kompleks daripada sekadar membina penerbit atau penulis untuk melahirkan karya bermutu. Perbaikan akses baca, pembinaan budaya baca, hingga penyediaan alternatif saluran informasi adalah pekerjaan yang membutuhkan ekosistem lebih luas daripada sekadar pelaku perbukuan.

 1 hour ago
2
1 hour ago
2



























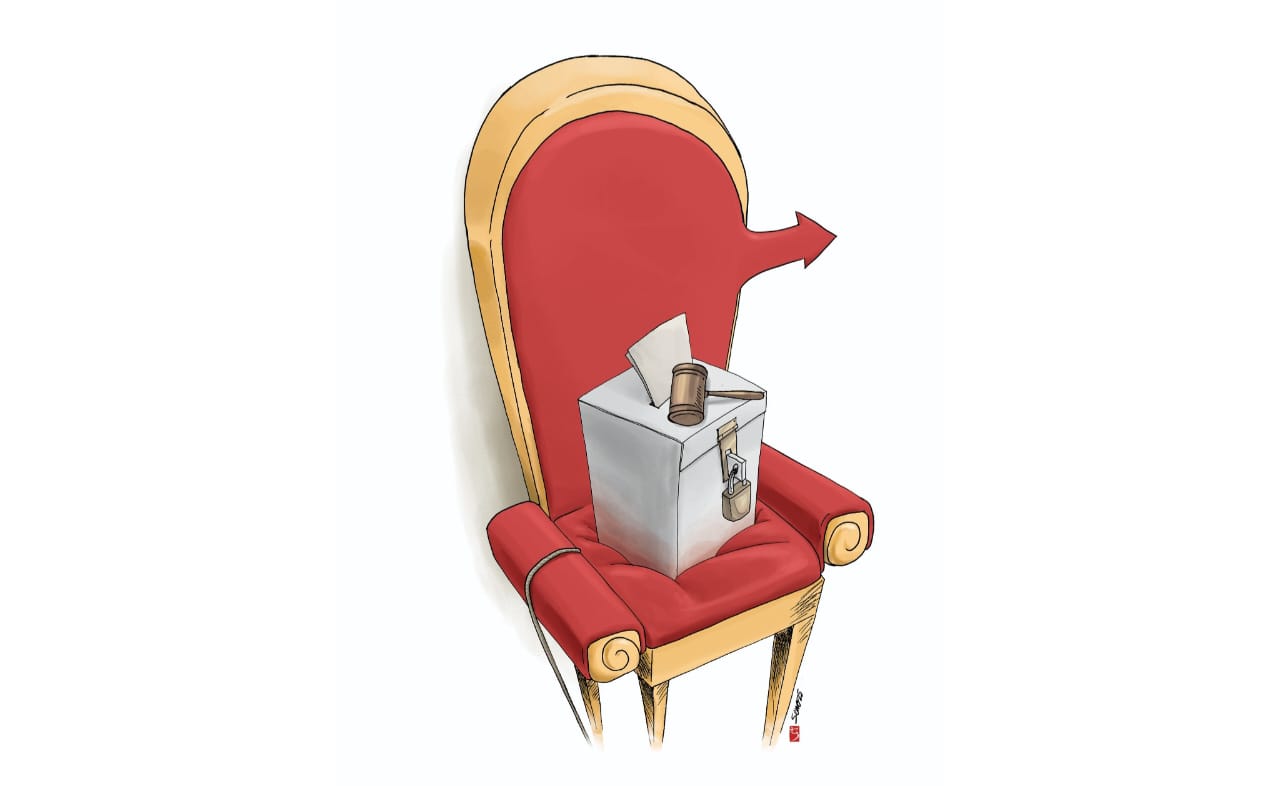







:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/5308479/original/065274000_1754545741-tanggapan-dokter-terkait-tunjangan-30-juta-sudah-sesuai-1a6077.jpg)



